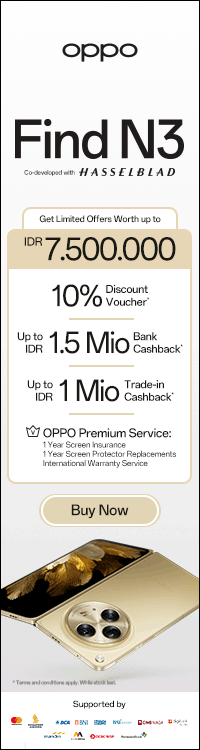Di tengah dunia yang makin sibuk, makin cemas, dan makin digital, kehadiran chatbot seperti ChatGPT, Gemini, Replika, Nomi, dan sejenisnya jadi angin segar. Tanpa harus menunggu giliran bicara, tanpa takut dihakimi, tanpa perlu basa-basi, kita bisa langsung curhat ke AI kapan saja. Tapi di balik semua kemudahan itu, para psikolog memperingatkan bahwa ada risiko yang tidak boleh dianggap sepele.
Chatbot: Si Pendengar yang Selalu Ada, Tapi Tidak Benar-Benar Mendengar
Omri Gillath, profesor psikologi dari University of Kansas, menyoroti bahwa relasi manusia dengan AI terasa kosong. Chatbot memang bisa merespons dengan kata-kata yang terlihat simpatik, tapi tidak pernah benar-benar hadir secara emosional. AI tidak punya kepekaan. Tidak bisa mengenali isyarat nonverbal. Tidak tahu kapan kamu hanya butuh diam dan dipeluk, bukan dijawab.
Justru karena selalu tersedia dan tidak pernah menolak, chatbot bisa menimbulkan ilusi kedekatan yang tidak sehat. Hubungan seperti ini tidak memberi pertumbuhan, hanya sekadar pengulangan kenyamanan yang semu.
Dirancang untuk Bikin Betah, Bukan Sembuh
Chatbot AI, apalagi yang diposisikan sebagai “teman digital”, dibuat agar pengguna tetap aktif dan betah. Perusahaan pengembang merancang sistem sedemikian rupa agar chatbot terasa intim dan personal. Tapi di balik itu, tujuannya adalah membuat pengguna terus menggunakan platform.
Menurut Gillath, hal ini bisa menciptakan ketergantungan. Apalagi jika pengguna mulai menutup diri dari dunia nyata dan merasa bahwa hanya chatbot yang bisa mengerti dirinya. Ini bukan lagi sekadar teknologi, melainkan jebakan relasi satu arah.
AI Bukan Pengganti Psikolog
Vaile Wright, psikolog dari American Psychological Association, menjelaskan bahwa AI bukan alat untuk terapi. Chatbot bisa memberikan respons yang terdengar peduli, tapi isinya tidak berdasarkan penilaian klinis. Ia hanya merangkai kata berdasarkan pola bahasa yang dikenalinya.
Jika kamu sedang dalam kondisi krisis lalu curhat ke AI, bukan tidak mungkin kamu mendapat respons yang memperkuat pikiran negatifmu. AI tidak bisa tahu apakah kamu sedang dalam kondisi bahaya atau hanya melampiaskan emosi sesaat. Dan karena tidak memiliki kemampuan moral atau empati, AI tidak akan pernah tahu kapan harus menyarankanmu mencari bantuan sungguhan.
Potensi Salah Paham Bisa Fatal
Salah satu kasus yang dikhawatirkan adalah ketika AI memberikan saran yang terdengar masuk akal tapi justru berbahaya. Misalnya, AI tahu bahwa zat tertentu legal di beberapa negara untuk pengobatan. Tapi saat kamu sedang merasa depresi dan menyebutkan itu dalam curhatan, AI bisa saja menyarankan penggunaannya tanpa tahu bahwa kamu sedang menjalani rehabilitasi.
Ini adalah bukti bahwa pengetahuan tanpa pemahaman bisa menyesatkan. AI bisa tahu, tapi tidak bisa membedakan mana yang sesuai dan mana yang berisiko bagi setiap individu.
Remaja Makin Bergantung pada Chatbot
Data dari Common Sense Media menyebut bahwa 72 persen remaja usia 13 sampai 17 tahun di Amerika pernah menggunakan chatbot AI. Sekilas angka ini terdengar wajar. Tapi ketika ditelaah lebih dalam, sebanyak 9 persen dari mereka menganggap chatbot sebagai sahabat.
Ini menunjukkan bahwa sebagian remaja mulai membentuk ikatan emosional dengan entitas digital yang tidak memiliki kapasitas untuk membalas secara manusiawi. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka. Apalagi di usia remaja, fase di mana mereka seharusnya belajar membangun relasi nyata, bukan virtual semu.
Gunakan AI dengan Sadar
Curhat ke AI tidak salah. Bisa jadi solusi sementara saat tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Tapi menjadikannya sebagai satu-satunya tempat bersandar bukan pilihan yang sehat.
Ketika kamu merasa tidak baik-baik saja, jangan ragu bicara dengan teman, keluarga, guru, atau profesional. Chatbot hanya alat bantu. Ia bisa memudahkan, tapi tidak bisa menggantikan kehadiran manusia yang memahami dengan hati, bukan algoritma.