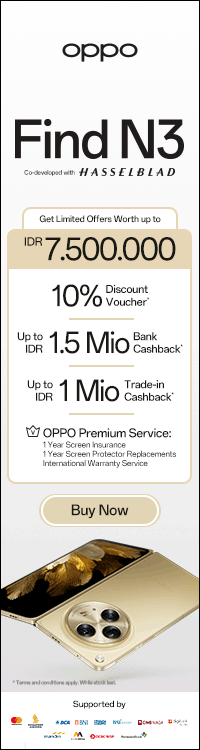Jakarta, 11 Agustus 2025 – Perbincangan tentang royalti musik di Indonesia kembali memuncak setelah dua peristiwa besar terjadi dalam waktu berdekatan. Pertama adalah penyelesaian sengketa antara jaringan kuliner Mie Gacoan di Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) yang berakhir damai dengan pembayaran Rp2,2 miliar. Kedua, munculnya foto struk restoran yang memuat biaya tambahan “Royalti Musik/Lagu” senilai Rp29.140 yang membuat banyak orang terkejut dan bertanya-tanya.
Kasus Mie Gacoan menjadi awal mula sorotan terhadap penerapan aturan royalti di industri kuliner. LMK SELMI menuduh restoran tersebut memutar musik secara komersial tanpa membayar royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, kedua pihak sepakat berdamai pada 8 Agustus 2025. Kesepakatan yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM itu mencakup pembayaran Rp2,2 miliar yang berlaku hingga Desember 2025. Perhitungan nilai ini mempertimbangkan jumlah gerai, kapasitas tempat duduk, dan periode pemutaran musik sejak 2022. Kasus ini menjadi preseden penting bahwa kewajiban royalti berlaku bagi semua usaha yang memanfaatkan musik secara komersial, tidak hanya untuk hotel atau pusat hiburan.
Beberapa hari setelah kesepakatan Mie Gacoan, publik kembali dihebohkan oleh foto struk restoran yang mencantumkan biaya royalti sebesar Rp29.140. Foto itu menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan sengit. Sebagian orang menganggap ini bentuk transparansi yang layak diapresiasi, namun tidak sedikit yang melihatnya sebagai beban tambahan yang tidak pantas dikenakan kepada pelanggan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) segera memberikan klarifikasi. Menurut PHRI, mencantumkan royalti musik secara terpisah di struk bukanlah praktik umum dalam industri restoran. Kewajiban membayar royalti sepenuhnya berada di tangan pengelola usaha dan biasanya sudah diperhitungkan dalam harga menu. PHRI juga menegaskan bahwa foto yang beredar bisa jadi kasus khusus dan tidak mencerminkan praktik industri secara keseluruhan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas mengatur bahwa penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial harus disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK yang sah, seperti SELMI. Besaran tarif royalti ditentukan oleh kapasitas tempat, jumlah kursi, serta durasi pemutaran musik. Dalam ketentuan ini, pelanggan tidak memiliki kewajiban membayar royalti secara langsung. Biaya tersebut merupakan bagian dari biaya operasional yang menjadi tanggung jawab pengusaha.
Organisasi perlindungan konsumen menilai bahwa penarikan royalti dari pelanggan tanpa penjelasan memadai dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi. Musik di restoran dianggap bagian dari layanan dan pengalaman makan yang seharusnya sudah termasuk dalam harga jual.
Polemik ini juga memunculkan kritik terhadap lembaga pengelola royalti. Beberapa musisi senior menilai perlunya pembenahan dalam mekanisme penarikan, distribusi, dan transparansi penggunaan dana. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar pelaku usaha memahami kewajiban mereka dan publik mengerti tujuan pembayaran royalti.
Dampak dari kasus ini mulai terlihat di industri kuliner. Beberapa restoran mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghentikan pemutaran musik demi menghindari beban biaya tambahan. Di sisi lain, kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan hak cipta semakin meningkat.
Isu royalti musik tahun ini menunjukkan bahwa regulasi sudah ada dan jelas, namun implementasi di lapangan memerlukan pendekatan yang lebih komunikatif dan proporsional. Keseimbangan antara kepatuhan hukum, edukasi publik, dan kenyamanan pelanggan menjadi kunci agar aturan ini berjalan tanpa menimbulkan polemik yang berkepanjangan.